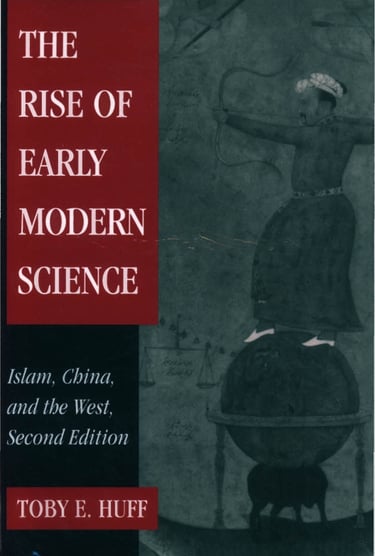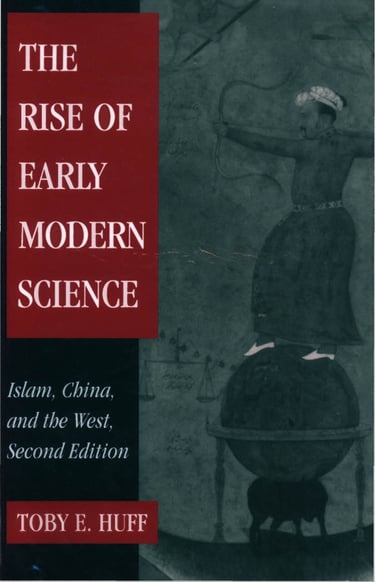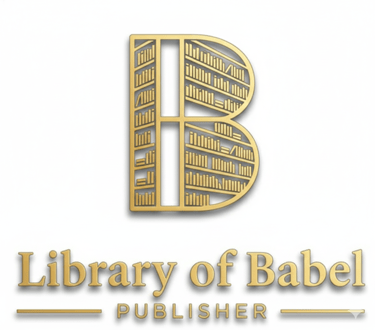Misteri Kebangkitan Sains Modern: Mengapa Barat, Bukan Timur?
1/29/20264 min read


Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa sains modern seperti yang kita kenal sekarang—dengan laboratoriumnya, metodenya yang ketat, dan dampaknya yang masif—lahir dan meledak di Barat (Eropa), dan bukan di peradaban lain? Padahal, jika kita menengok sejarah, dunia Islam dan Cina memiliki peradaban yang jauh lebih tua dan canggih pada masanya.
Sosiolog Toby E. Huff dalam karyanya The Rise of Early Modern Science: Islam, China, and the West (2003)—mengajak kita menyelami pertanyaan fundamental ini. Karya tersebut tak sekadar membahas sejarah penemuan, melainkan juga menggali “perangkat lunak” (software) peradaban: hukum, teologi, dan institusi yang memungkinkan sains tumbuh subur.
Paradoks “Keterlambatan” Barat dan Keunggulan Awal Islam
Hingga abad ke-12 dan ke-13, sains Arab-Islam sebenarnya jauh lebih maju jika dibandingkan dengan sains di Barat. Peradaban Islam adalah pemegang obor pengetahuan ketika Eropa masih meraba-raba dalam kegelapan.
Namun, sejarah kemudian berbelok tajam.
Sains modern, sebagai sebuah institusi yang unik dan revolusioner, hanya muncul di Barat. Huff mencatat bahwa jika kita menghitung mundur, pengejaran sains di Barat telah berlangsung tanpa henti selama hampir 900 tahun, dimulai dari kebebasan berpikir yang muncul di universitas-universitas abad ke-12 dan ke-13.
Pertanyaan besarnya adalah: apakah sains modern ini hanyalah “fenomena” Barat semata? Atau apakah ada prinsip-prinsip universal yang membuat masyarakat Barat mampu melembagakan cara berpikir ini? Huff menantang kita untuk melihat bahwa keberhasilan ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari struktur sosial yang sangat spesifik.
Sains sebagai “Musuh Alami” Otoritas
Salah satu poin paling menarik dan provokatif dalam karya Huff ini adalah definisi sosiologis tentang sains itu sendiri. Sains bukan sekadar mengumpulkan fakta. Ia adalah sebuah “pengembaraan imajinasi” yang didasari oleh gagasan bahwa dunia ini rasional dan teratur, serta manusia adalah makhluk rasional yang mampu memahaminya.
Namun, sifat dasar sains adalah pemberontak. Huff menyebutkan bahwa sains adalah “musuh alami” dari segala kepentingan yang mapan (vested interests), baik itu kepentingan sosial, politik, maupun agama—bahkan termasuk kemapanan ilmiah itu sendiri. Mengapa? Ini karena pikiran ilmiah menolak untuk membiarkan segala sesuatu tetap seperti apa adanya.
Etos sains adalah “keraguan yang terorganisasi” (organized skepticism). Ia selalu meragukan konsensus intelektual, baik yang terbaru maupun yang sudah lama bertahan. Karena mandat intelektualnya adalah menyelidiki segala bentuk eksistensi, sains menjadi musuh utama bagi rezim otoriter. Rezim semacam itu hanya bisa bertahan jika mereka menindas penyelidikan ilmiah yang dapat mengungkapkan konsekuensi sebenarnya dari kekuasaan mereka, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik.
Fakta ini memberi wawasan penting bagi kita: kebangkitan sains modern membutuhkan “zona netral” kebebasan penyelidikan yang dilindungi, sesuatu yang berhasil diciptakan oleh institusi Barat namun sulit dipertahankan di tempat lain.
Peran Tersembunyi Hukum dan Teologi
Inilah bagian yang paling menarik bagi pembaca. Kita sering mengira sains hanya berurusan dengan teleskop atau tabung reaksi. Namun, Huff berargumen bahwa akar dari sains modern justru tertanam dalam Hukum dan Teologi. Dalam diagram “Domain Proses Sosial” yang disajikan, Huff menempatkan “Hukum dan Pemikiran Hukum” serta “Teologi dan Filsafat Alam” sebagai fondasi yang membentuk “Rasionalitas”, yang kemudian melahirkan sains modern.
Hukum sebagai Pembentuk Pola Pikir
Huff memberikan prioritas utama pada hukum. Dalam peradaban Islam klasik, hukum (syariah) adalah struktur pengarah yang paling utama. Di Barat, hukum juga penting tetapi memiliki “warna” yang sangat berbeda dan progresif. Revolusi dalam struktur hukum Barat ternyata memiliki dampak luar biasa dalam membentuk pengalaman intelektual mereka.
Mengapa hukum begitu penting bagi sains? Ini karena sistem hukum mengajarkan cara berpikir. Hukum menetapkan “kanon penyelidikan rasional” dan batas-batas penyelidikan yang sah. Cara sebuah peradaban menyelesaikan sengketa hukum mencerminkan cara mereka menggunakan nalar/rasio. Di Cina, konsep hukum sebaliknya memainkan peran yang jauh lebih kecil, yang mungkin menjelaskan perbedaan lintasan sejarah sains di sana.
Teologi dan Citra Keteraturan
Sama halnya dengan hukum, teologi juga memainkan peran kunci. Meskipun sains modern sering dianggap menggoncang pandangan agama, Huff mencatat bahwa beberapa sistem teologis justru mengandung citra keteraturan dan proses sistematis yang kondusif bagi perkembangan sains.
Teologi membentuk konsep tentang “rasio” dan “rasionalitas”. Asumsi-asumsi metafisika dalam teologi tertentu ternyata sangat subur untuk mendorong pemikiran ilmiah. Sebaliknya, ketiadaan teologi dalam arti yang ketat di Cina menjadi faktor penting yang membedakan sejarah pemikiran mereka.
Institusi: Laboratorium Rasionalitas
Gagasan-gagasan tentang hukum dan teologi tersebut bukanlah hal abstrak tanpa pijakan. Semua itu membutuhkan wadah. Di sinilah peran “struktur institusional”. Institusi adalah tempat di mana konsep rasionalitas dipraktikkan.
Huff menyoroti bahwa sosiolog sering lupa memperhatikan “struktur dalam” dari institusi sosial. Di Barat, institusi-institusi ini (seperti universitas) berkembang menjadi entitas yang dinamis dan bahkan revolusioner, yang mampu membentuk ulang tatanan sosial dan politik. Studi tentang kebangkitan sains modern, pada hakikatnya, adalah studi tentang pembangunan institusi (institution building). Karya Huff menjanjikan analisis perbandingan yang tajam antara universitas di Barat dan madrasah di dunia Islam, serta bagaimana implikasi hukum dan filosofis yang berbeda di kedua institusi tersebut mempengaruhi nasib sains.
Rasionalitas: Lebih dari Sekadar Sains
Fakta menarik lainnya adalah hubungan antara sains dan aspek budaya lainnya. Penulis merujuk pada pemikiran Max Weber, sosiolog ternama, yang melihat adanya hubungan antara kebangkitan sains modern dengan kebangkitan kapitalisme. Keduanya hanya muncul secara unik di Barat.
Namun, yang lebih menarik adalah contoh di bidang seni. Weber menunjukkan bahwa musik di Barat juga mengalami proses “rasionalisasi” yang unik. Musik polifoni (banyak suara), sistem temperamen yang setara (tangga nada), dan orkestra simfoni adalah ciptaan unik Barat yang lahir dari dorongan rasionalisasi yang sama dengan yang melahirkan sains.
Ini menunjukkan bahwa sains modern bukan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari paket besar “kepercayaan pada rasio” yang diterapkan ke seluruh domain kehidupan, mulai dari mempelajari alam hingga menggubah musik.
Kesimpulan: Tantangan Masa Depan
Huff menutup karyanya dengan sebuah renungan tentang masa depan global. Saat kita memasuki dunia yang semakin terglobalisasi, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sangat krusial.
Apakah negara-negara berkembang akan mengizinkan warganya untuk berpartisipasi penuh dalam “alam pikiran” (realms of the mind)—baik itu sains, politik, maupun sastra? Atau apakah mereka akan terus mendirikan tembok penghalang bagi kebebasan berpikir demi kepentingan identitas etnis atau agama?
Penulis mencatat bahwa sebagian Asia, terutama Asia Tenggara, tampaknya siap untuk melangkah maju, meskipun masih banyak kekuatan yang menentang keterbukaan tersebut. Perjuangan untuk kebangkitan global ini sedang berlangsung, dan prasyarat modernitas ini masih harus dicapai oleh sebagian besar penduduk dunia.
Sumber Bacaan:
Huff, Toby E. 2003. The Rise of Early Modern Science: Islam, China, and the West (Second Edition). Cambridge: Cambridge University Press.