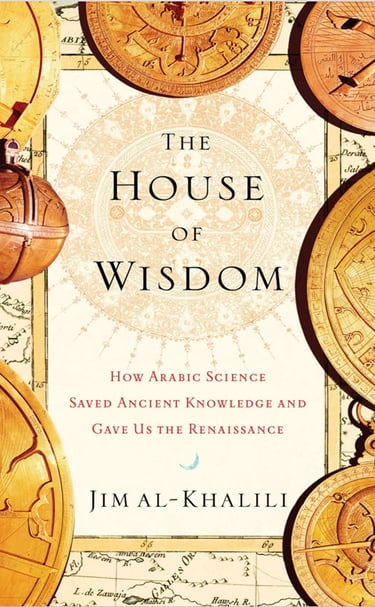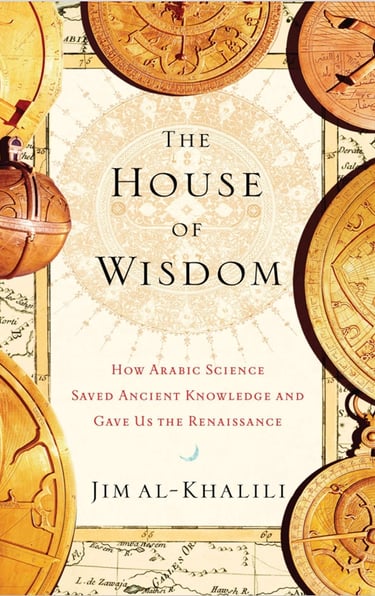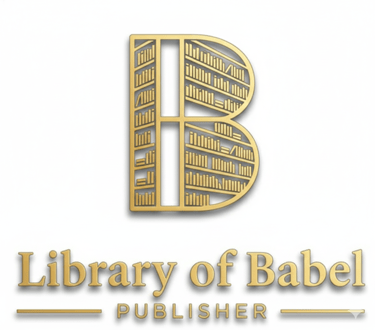Mimpi Aristoteles dan Kebangkitan Baghdad
12/15/20257 min read


Di pusat kota Baghdad modern, terdapat sebuah distrik bernama Bab al-Sharqi. Nama ini berarti “Gerbang Timur”. Nama ini adalah satu-satunya pengingat yang tersisa dari benteng pertahanan abad pertengahan yang pernah melindungi kota ini. Tembok-tembok ini dulu dibangun sekitar paruh pertama abad ke-10 namun kini tak ada satu pun batunya yang tersisa.
Bagi mereka yang mengingat Baghdad sebelum perang modern, Bab al-Sharqi dikenal sebagai alun-alun yang panas, bising, penuh sesak dengan aroma makanan kaki lima, dan hiruk-pikuk toko piringan hitam bekas di sekitar terminal bus. Namun, di balik kebisingan itu, tersembunyi jejak sejarah dari sebuah kota yang pernah menjadi pusat kekuasaan Kekaisaran Abbasiyah yang perkasa sejak didirikan pada 762 Masehi.
Sejarah Baghdad adalah sejarah tentang kebangkitan dan kehancuran yang berulang. Tidak ada kota lain di muka bumi ini yang harus menanggung tingkat kematian dan kehancuran seperti yang dialami Baghdad selama berabad-abad. Namun, sebelum semua penderitaan itu, Baghdad pernah menjadi kota terkaya, terbesar, dan paling angkuh di planet ini selama setengah milenium.
Di sinilah, tepatnya dua belas abad setelah kota ini didirikan, kisah kita bermula—sebuah kisah tentang seorang penguasa yang mimpinya mengubah wajah dunia ilmu pengetahuan selamanya.
Bayang-Bayang Sang Ayah: Harun al-Rashid
Untuk memahami kebangkitan intelektual Baghdad, kita harus melihat ke masa lalu, ke era Khalifah Harun al-Rashid (763-809 M). Nama Harun al-Rashid mungkin terdengar akrab bagi kita karena ia sering muncul sebagai tokoh dalam kisah dongeng “Seribu Satu Malam”. Dalam sejarah Barat, ia dikenal sebagai penguasa yang menjalin hubungan diplomatik dengan Kaisar Eropa, Charlemagne.
Hubungan antara Harun al-Rashid dan Charlemagne adalah hubungan antara dua orang paling berkuasa di zamannya. Mereka saling bertukar hadiah luar biasa mewah. Charlemagne mengirimkan kain wol Frisian ke Baghdad sementara, sebagai balasannya, al-Rashid mengirimkan sutra Abbasiyah, batuan kristal, dan benda-benda mewah lain. Bahkan, al-Rashid pernah mengirimkan seekor gajah dan sebuah jam air dari kuningan yang rumit, yang pastinya membuat kaisar Eropa itu terperangah. Kekayaan Harun al-Rashid begitu melegenda hingga ia dikabarkan pernah membeli sebuah mutiara terkenal bernama “al-Yatima” seharga 70.000 dinar emas.
Namun, Harun al-Rashid bukan hanya seorang raja kaya raya. Ia juga pemimpin militer agresif. Ia memimpin banyak ekspedisi militer melawan Kekaisaran Bizantium. Ketika Kaisar Bizantium Nicephorus I menolak membayar upeti, al-Rashid merespons dengan invasi besar-besaran. Pada 806 M, ia menyerbu Asia Kecil dengan lebih dari 135.000 pasukan, memaksa Nicephorus untuk menyerah dan membayar upeti tahunan sebesar 30.000 koin emas.
Meskipun zaman Harun al-Rashid sering dikenang dengan nostalgia sebagai puncak keemasan Baghdad, kenyataannya sedikit lebih rumit. Ia sebenarnya administrator yang buruk dan sangat bergantung pada keluarga Persia yang kuat bernama Barmaki (atau Barmakids) untuk menjalankan urusan negara. Di balik kemegahan istananya, benih-benih perpecahan yang akan menghancurkan kota itu mulai tumbuh.
Dua Putra, Dua Nasib: Al-Amin dan Al-Ma’mun
Harun al-Rashid memiliki dua putra yang ditakdirkan untuk tumbuh di dunia yang sangat berbeda meskipun lahir hanya berselisih enam bulan. Putra pertamanya, Abdullah—yang kelak bergelar “Al-Ma’mun—lahir pada 786 M, tahun yang sama ketika Harun menjadi khalifah.
Kelahiran Al-Ma’mun diselimuti oleh kisah tragis dan ironis. Ibunya, Marajil, adalah selir budak Persia yang awalnya dibawa ke Baghdad sebagai tawanan perang. Marajil bekerja di dapur istana dan dianggap sebagai budak “paling jelek dan kotor”. Namun, istri sah Harun yang berdarah Arab murni, Zubayda, dalam sebuah taruhan catur, memaksa suaminya untuk tidur dengan Marajil sebagai hukuman karena kalah bermain. Dari hubungan paksaan inilah lahir Al-Ma’mun, seorang anak setengah Arab dan setengah Persia, yang ibunya meninggal tak lama setelah melahirkannya.
Di sisi lain, enam bulan setelah kelahiran Al-Ma’mun, Zubayda melahirkan putra kedua bagi Harun, yang diberi nama “Al-Amin”. Berbeda dengan kakaknya, Al-Amin memiliki darah bangsawan Arab murni dari kedua orang tuanya—menjadikannya penerus "alami" takhta kekhalifahan di mata para bangsawan Arab.
Al-Ma’mun dibesarkan di bawah asuhan keluarga Barmaki. Ia tumbuh menjadi pemuda cerdas dan haus ilmu. Ia menghafal Al-Qur’an, mempelajari sejarah Islam, puisi, tata bahasa Arab, aritmatika, dan yang paling penting, mendalami filsafat dan teologi. Kecintaannya pada ilmu ini kelak akan memainkan peran besar dalam obsesinya terhadap sains. Sebaliknya, Al-Amin tumbuh menjadi sosok dangkal dan kurang cakap dalam memimpin.
Protokol Mekkah dan Benih Perang Saudara
Pada 802 M, saat melakukan ibadah haji ke Mekkah, Harun al-Rashid membuat keputusan fatal mengenai pewarisan takhtanya. Ia mengumumkan bahwa Al-Amin akan menjadi khalifah di Baghdad sementara Al-Ma’mun akan menjadi penguasa berdaulat atas provinsi-provinsi timur kekaisaran di Khurasan, dengan pusat pemerintahan di kota Merv. Sumpah setia kedua putranya dicatat dalam dokumen yang disimpan di dalam Ka’bah, yang dikenal sebagai “Protokol Mekkah”.
Harun al-Rashid sebenarnya tahu bahwa Al-Ma’mun yang setengah Persia adalah pemimpin yang jauh lebih baik—lebih cerdas, lebih bertekad, dan memiliki penilaian yang lebih sehat. Namun, tekanan dari Zubayda dan kaum elite Arab memaksanya memilih Al-Amin. Keputusan ini, disengaja atau tidak, menanam benih kehancuran. Pemberian wilayah Khurasan kepada Al-Ma’mun bukan sekadar hadiah hiburan. Itu adalah basis kekuatan yang memungkinkan Al-Ma’mun untuk kelak menantang saudaranya.
Ketegangan memuncak ketika Harun al-Rashid meninggal pada 809 M saat sedang dalam perjalanan memadamkan pemberontakan di Khurasan. Kematian sang ayah memicu rangkaian peristiwa yang tak terelakkan. Al-Amin, yang kemudian menjadi khalifah di Baghdad, mulai melanggar perjanjian suksesi dengan menunjuk putranya sendiri sebagai penerus dan menuntut pendapatan pajak dari Khurasan. Al-Ma’mun, yang saat itu berusia 23 tahun dan telah berhasil memadamkan pemberontakan di wilayahnya, merespons Al-Amin dengan memotong jalur komunikasi dan mempersiapkan pasukan.
Pengepungan Baghdad: Runtuhnya Kota Bundar
Konflik dua saudara ini segera berubah menjadi perang terbuka. Pasukan Al-Ma’mun, yang dipimpin oleh Jenderal Tahir, bergerak ke barat dan mengepung Baghdad pada April 812 M. Pengepungan ini menjadi malapetaka bagi Baghdad. Selama lebih dari satu tahun, kota yang dulunya megah itu digempur tanpa ampun. Pasukan Tahir menggunakan ketapel raksasa untuk menghancurkan tembok dan bangunan sementara pasukan Al-Amin membakar seluruh lingkungan perumahan untuk memperlambat gerak musuh. Al-Amin sendiri berlindung di dalam “Kota Bundar” (Round City), benteng tua yang dibangun oleh leluhurnya, Al-Mansur.
Penyair Baghdad abad kesembilan, Abu Tammam, menggambarkan kehancuran ini dengan pilu: “sang pembawa berita kematian telah bangkit untuk meratapi Baghdad,” membandingkan kota itu dengan “seorang wanita tua yang masa mudanya telah meninggalkannya, dan yang kecantikannya telah sirna”.
Akhir dari perang saudara ini sangat brutal. Pada musim gugur 813 M, pertahanan Baghdad runtuh. Al-Amin ditangkap oleh pasukan Tahir. Ada beberapa versi mengenai kematiannya. Salah satu kisah yang paling mengerikan menyebutkan bahwa ketika Tahir meminta petunjuk kepada Al-Ma’mun tentang apa yang harus dilakukan terhadap saudaranya, Al-Ma’mun mengirim sebuah baju tanpa lubang leher—isyarat untuk memenggal kepala Al-Amin. Kepala Al-Amin kemudian dikirim sejauh 1.000 mil ke Merv dan dipajang di halaman istana Al-Ma'mūn. Versi lain yang lebih simpatik mengatakan bahwa eksekusi itu adalah inisiatif Tahir sendiri, dan Al-Ma’mun menangis serta berduka saat menerima kepala saudaranya.
Kehidupan di Baghdad: Kemewahan dan Kesederhanaan
Sebelum pengepungan pasukan Al-Ma’mun tersebut, Baghdad merupakan metropolis besar pada masa itu, bahkan mungkin yang terbesar di dunia dengan populasi lebih dari satu juta jiwa. Istana-istana megah berjejer di tepian Sungai Tigris. Bangunan-bangunan ini, termasuk istana khalifah, dibangun dari batu bata lumpur yang dikeringkan matahari, karena tidak ada tambang batu di Irak. Namun, interiornya sangat mewah. Lantai marmer, ubin keramik, dan permadani indah menghiasi rumah-rumah orang kaya. Untuk mengatasi panas di musim panas yang menyengat, keluarga-keluarga kaya tidur di atap datar pada malam hari dan beristirahat di ruang bawah tanah yang sejuk (sirdab) pada siang hari.
Sebaliknya, rakyat miskin tinggal di bangunan bertingkat yang padat, dengan lantai yang dipisahkan oleh batang pohon palem. Sebuah catatan tuan tanah dari abad ke-9 mengeluhkan perilaku penyewa yang memasak di atap (berisiko kebakaran), menyumbat saluran air, dan mencuri tangga saat pindah rumah. Meski ada kesenjangan, kota ini dikelola dengan baik; jalan-jalannya bersih, kanal-kanalnya rumit, dan udaranya dipenuhi aroma rempah-rempah serta bau khas ikan mas bakar (shabbout) yang masih populer hingga hari ini.
Kembalinya Al-Ma’mun dan Era Baru Pengetahuan
Al-Ma’mun kembali ke Baghdad pada 819 M, enam tahun setelah kematian saudaranya. Kota yang sempat hancur itu kemudian dibangun kembali. Kedatangan Al-Ma’mun menandai dimulainya era baru.
Berbeda dengan Al-Amin yang tradisionalis, Al-Ma’mun adalah pendukung kuat gerakan rasionalis yang dikenal sebagai Mu’tazilah. Aliran ini menekankan pada akal, pertanyaan terbuka, dan kehendak bebas, serta menentang interpretasi harfiah terhadap Al-Qur’an. Di bawah naungan Al-Ma’mun, Baghdad menjadi magnet bagi para sarjana dari seluruh kekaisaran. Semangat toleransi dan keterbukaan terhadap agama dan budaya lain berkembang pesat, menciptakan suasana optimisme intelektual yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Salah satu penulis terkenal Baghdad, Al-Jahiz, menulis dalam bukunya Kitab Al-Hayawan tentang pentingnya kebijaksanaan kuno: “Bagian kita akan kebijaksanaan akan sangat berkurang... seandainya orang-orang kuno (Yunani) tidak melestarikan bagi kita kebijaksanaan mereka yang luar biasa.”
Namun, toleransi Al-Ma’mun tetap memiliki batas. Di akhir hidupnya, ia melancarkan inkuisisi (mihna) terhadap kaum konservatif Islam yang menolak doktrin Mu’tazilah.
Mimpi Aristoteles: Titik Balik Sejarah Sains
Momen paling menentukan dalam kehidupan intelektual Al-Ma’mun—dan mungkin dalam sejarah sains dunia—konon bermula dari sebuah mimpi. Sejarawan abad kesepuluh, Ibn al-Nadim, mencatat kisah ini dalam bukunya Fihrist. Pada suatu malam, Al-Ma’mun bermimpi melihat seorang pria berkulit putih kemerahan, berdahi tinggi, beralis tebal, berkepala botak, dan bermata biru tua sedang duduk di kursi.
Dalam mimpi itu, Al-Ma’mun bertanya dengan penuh kekaguman, “Siapakah engkau?”
Pria itu menjawab, “Saya Aristoteles.”
Al-Ma’mun bertanya lagi, “Wahai filsuf, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan?”
“Tanyalah,” jawab Aristoteles.
“Apakah yang baik itu?” tanya Al-Ma’mun.
Aristoteles menjawab, “Apa pun yang baik menurut akal (intelek).”
“Lalu apa?” kejar Al-Ma’mun.
“Apa pun yang baik menurut pendapat orang banyak,” jawab sang filsuf.
“Lalu apa?”
“Lalu, tidak ada lagi ‘lalu’.”
Meskipun kisah mimpi ini diragukan kebenarannya, dampaknya sangat nyata. Al-Ma’mun mendedikasikan sisa hidupnya untuk mengejar “apa pun yang baik menurut akal”. Ia menjadi terobsesi untuk menerjemahkan teks-teks kuno dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab.
Mimpi ini menjadi simbol lahirnya gerakan penerjemahan besar-besaran yang memicu Zaman Keemasan Sains Islam. Al-Ma’mun menciptakan lingkungan yang mendorong pemikiran orisinal dan debat bebas, yang memungkinkan lahirnya para jenius sains Arab generasi pertama. Penyatuan antara rasionalisme Yunani dan teologi Mu’tazilah melahirkan gerakan humanis yang skalanya tidak akan terlihat lagi hingga masa Renaisans Italia di abad ke-15.
Warisan yang Abadi
Kisah Al-Ma’mun mengajarkan kepada kita bahwa kemajuan peradaban tak jarang lahir dari perpaduan kompleks antara ambisi kekuasaan, konflik berdarah, dan dahaga akan pengetahuan. Baghdad, yang pernah hancur lebur akibat perang antara dua saudara, bangkit kembali menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dunia berkat visi seorang pemimpin yang percaya bahwa akal manusia adalah anugerah tertinggi.
Hari ini, ketika melihat kembali reruntuhan sejarah di Bab al-Sharqi atau membaca kejayaan masa lalu Baghdad, kita diingatkan bahwa meskipun tembok benteng bisa runtuh dan istana bisa hancur menjadi debu, warisan ilmu pengetahuan yang dibangun di atas fondasi “Mimpi Aristoteles” tetap abadi, mengalir melalui nadi peradaban modern kita hingga detik ini.
Sumber bacaan:
Al-Khalili, Jim. 2011. The House of Wisdom: How Arabic Science Saved Ancient Knowledge and Gave Us the Renaissance. New York: The Penguin Press.